INTO THIN AIR - Kisah Tragis Pendaki Everest (Part 2 - Bab I Puncak Everest...bersambung)
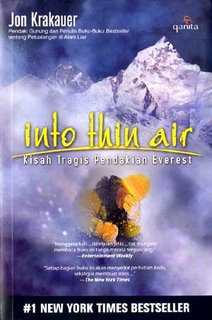
SATU
PUNCAK EVEREST
10 MEI 1996
29.028 KAKI
Seolah sebuah benteng yang sangat kukuh melindungi puncak-puncak gunung yang megah itu, tempat yang tidak terjamah oleh tangan manusia. Kenyataannya adalah, pada ketinggian 25.000 kaki atau lebih, tekanan udara yang sangat rendah bisa berakiat fatal pada tubuh manusia sehingga pendakian hampir-hampir mustahil dilakukan, dan badai yang paling lunak sekalipun bisa mengakibatkan kematian. Hanya jika cuaca dan salju benar-benar sempurna, maka muncul sedikit peluang untuk berhasil, dan bahkan pada tahap terakhir pendakian, tak satu pun kelompok pendaki bakal bisa memilih hari mereka.
Tidak, sungguh tidak aneh jika Everest tidak bisa segera ditaklukkan; justru mengejutkan, dan sedikit menyedihkan jika hal sebaliknya yang terjadi, karena itu bukanlah sifat sebuah gunung yang hebat. Barangkali kita telah menjadi sedikit sombong karena adanya teknik baru untuk mencengkeram es, dan sepatu karet, atau karena berbagai temuan baru di bidang mekanik. Kita lupa, bahwa gunung itu masih tetap memegang kuasa, dia akan memberi kita peluang meraih sukses pada waktu yang dia tetapkan sendiri.Jika tidak, pesona apa lagi yang akan tersisi dalam pendakian gunung ?
Eric Shipton, 1938
Upon That Mountain
Berdiri di atas puncak dunia, satu kaki di wilayah Cina dan satu lagi di wilayah Nepal, aku membersihkan butiran-butiran es dari masker oksigenku. Dengan bahu membungkuk karena terjangan angin, aku memandang tanpa sadar ke bawah, ke arah dataran Tibet yang luas. Samar-samar dan tanpa pemahaman penuh, aku menyadari bahwa bumi yang terhampar di bawah kakiku merupakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Selama berbulan-bulan aku selalu memimpikan saat-saat seperti ini, serta luapan emosi yang menyertainya. Namun sekarang, setelah akhirnya aku tiba di tempat ini, ketika aku benar-benar berdiri di Puncak Everest, aku hampir-hampir tidak memiliki energi peduli itu semua.
Saat itu siang hari, 10 Mei 1996. Aku belum tidur selama lima puluh tujuh jam. Satu-satunya makanan yang mampu kutelan dalam tiga hari terkahir hanyalah sup ramen dan segengam cokelat kacang M&M. Batuk hebat yang menyerangku selama dua minggu terakhir membuat dua tulang rusukku bergeser, sehingga bernapas normal pun terasa sangat menyakitkan. Pada ketinggian troposfer 29.028 kaki, sangat sedikit oksigen yang bisa masuk ke dalam otakku sehingga kapasitas mentalku sama dengan kapasitas mental seorang anak yang terbelakang. Dalam kondisi seperti itu, aku hampir-hampir tidak bisa merasakan apa-apa kecuali rasa dingin dan lapar.
Aku tiba di uncak ini beberapa menit setelah Annatoli Boukreev, seorang pemandu gunung asal Rusia yang bekerja untuk sebuahh perusahaan pendaki gunung komersial milik warga Amerika, dan hanya beberapa saat sebelum Andy Harris, seornag pemandu untuk sebuah tim yang berbasis di Selandia Baru, yaitu kelompokku sendiri. Aku kurang mengenal Boukreev, tetapi aku mulai akrab dan menyukai Harris selama enam minggu terakhir ini. Dengan cepat aku mengambil empat foto Harris dan Boukreev yang sedang berpose di puncak gunung, berbalik dan kembali menuruni gunung. Jam tanganku menunjukkan pukul 13.17. Total, aku berada di atap dunia itu hanya selama kurang lima menit.
Beberapa menit kemudian, aku berhenti lagi untuk mengambil foto, kali ini kamera kuarahkan ke bawah, ke arah lereng Tenggara, rute yang kami lalui saat mendaki. Ketika aku sedang mengarahkan teropongku pada sekelompok pendaki yang sedang bergerak ke puncak, aku menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatianku. Di arah selatan, yang sejam lalu masih berlangit biru cerah, kini diselimuti awan gelap, termasuk di atas Pumori, Ama Dablam, dan beberapa puncak yang lebih rendah dari Everest.
Lama kemudian – setelah enam tubuh yang tak bernyawa berhasil ditemukan, setelah upaya pencarian dua pendaki yan hilang dihentikan, setelah ahli bedah memotong kaki rekan satu timku, Beck Weathers, karena membusuk – orang-orang mulai bertanya-tanyam jika cuaca benar-benar mulai memburuk, mengapa para pendaki yang berada di lereng yang lebih tinggi mengabaikan tanda-tanda tersebut ? Mengapa para veteran pemandu Gunung Himalaya terus mendaki, memandu sekelompok pendaku yang relatif belum berpengalaman – yang masing-masing sudah mengeluarkan 65 ribu dolar agar dituntun dengan selamat sampai ke Puncak Everest – menuju perangkap kematian yang tampak begitu jelas ?
Tidak ada yang bisa menjawab atas nama dua pemandu yang mempimpin kedua tim tersebut karena keduanya sudah tewas. Namun, berdasarkan pengamatanku pada siang hari, 10 Mei tersebut, aku bisa mengatakan bahwa tidak ada satu tanda pun yang menunjukkan bahwa badai mematikan sedang mengancam. Dalam otakku yang sudah kehabisan oksigen, awan yang membubung di atas lembah es yang indah yang dikenal sebagai Cwm (baca Koom) Barat[1] sama sekali tidak berbahaya, halus dan tidak pekat. Berkilat di bawah sinar matahari siang, awan-awan itu lebih menyerupai kondensasi uap air yang naik dar lembah, seperti yang selalu terjadi hampir setiap sore hari.
[1] Nama Cwm Barat, diucapkan kum, diberikan oleh George Leigh Mallory yang melihatnya untuk pertama kali saat melakukan ekspedisi pertama ke Everest pada 1921 dari Lho La, sebuah jalan di atas gunung yang terletak di perbatasan antara Nepal dan Tibet. Cwm adalah istilah yang berasa dari bahasa Welsh yang berarti lembah atau cekungan yang sangat dalam.





0 Comments:
Post a Comment
<< Home